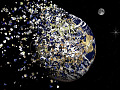Bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik dan memuaskan?
Aristoteles pertama kali mengajukan pertanyaan ini dalam bukunya Etika Nicomachean – bisa dibilang ini adalah pertama kalinya seseorang dalam sejarah intelektual Barat memusatkan perhatian pada subjek ini sebagai pertanyaan yang berdiri sendiri.
Dia merumuskan tanggapan teleologis terhadap pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Aristoteles mengusulkan, dengan kata lain, suatu jawaban yang didasarkan pada penyelidikan atas tujuan atau tujuan kita (telos) sebagai suatu spesies.
Tujuan kita, menurutnya, dapat diungkapkan melalui studi tentang esensi kita – ciri mendasar dari apa artinya menjadi manusia.
Tujuan dan esensi
“Setiap keterampilan dan setiap penyelidikan, dan demikian pula setiap tindakan dan pilihan rasional, dianggap bertujuan untuk kebaikan;” Aristoteles menyatakan, “sehingga kebaikan dengan tepat digambarkan sebagai tujuan segala sesuatu.”
Untuk memahami apa yang baik, dan oleh karena itu, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai kebaikan, pertama-tama kita harus memahami hal-hal seperti apa diri kita. Ini akan memungkinkan kita menentukan fungsi yang baik atau buruk.
Bagi Aristoteles, ini adalah kebenaran yang berlaku umum. Ambil pisau, misalnya. Pertama-tama kita harus memahami apa itu pisau untuk menentukan apa fungsi sebenarnya dari pisau tersebut. Inti dari sebuah pisau adalah ia memotong; itulah tujuannya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa pisau tumpul adalah pisau yang buruk – jika tidak dipotong dengan baik, maka dalam arti penting pisau tersebut gagal memenuhi fungsinya dengan baik. Beginilah esensi berkaitan dengan fungsi, dan bagaimana pemenuhan fungsi tersebut memerlukan semacam kebaikan bagi benda yang bersangkutan.
Tentu saja menentukan fungsi pisau atau palu jauh lebih mudah dibandingkan menentukan fungsinya homo sapiens, dan oleh karena itu kehidupan yang baik dan memuaskan apa yang mungkin terjadi bagi kita sebagai suatu spesies.
Aristoteles berpendapat bahwa fungsi kita harus lebih dari sekadar pertumbuhan, nutrisi, dan reproduksi, karena tumbuhan juga mampu melakukan hal tersebut. Fungsi kita juga harus lebih dari sekedar persepsi, karena hewan non-manusia mampu melakukan hal ini. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa esensi kita – yang membuat kita unik – adalah bahwa manusia mampu berpikir.
Oleh karena itu, apa yang tercakup dalam kehidupan manusia yang baik dan berkembang adalah “semacam kehidupan praktis dari bagian yang memiliki alasan”. Inilah titik tolak etika Aristoteles.
Kita harus belajar bernalar dengan baik dan mengembangkan kebijaksanaan praktis dan, dalam menerapkan alasan ini pada keputusan dan penilaian kita, kita harus belajar menemukan keseimbangan yang tepat antara kelebihan dan kekurangan kebajikan.
Hanya dengan menjalani kehidupan “kegiatan bajik yang sesuai dengan akal budi”, suatu kehidupan di mana kita berkembang dan memenuhi fungsi-fungsi yang mengalir dari pemahaman mendalam dan penghargaan atas apa yang mendefinisikan kita, maka kita dapat mencapainya. eudaimonia – kebaikan manusia tertinggi.

Sekolah Athena – Raphael (1509). Public domain
Eksistensi mendahului esensi
Jawaban Aristoteles begitu berpengaruh hingga membentuk perkembangan nilai-nilai Barat selama ribuan tahun. Terima kasih kepada para filsuf dan teolog seperti Thomas Aquinas, pengaruhnya yang bertahan lama dapat ditelusuri melalui periode abad pertengahan hingga Renaisans dan hingga Pencerahan.
Selama masa Pencerahan, tradisi filsafat dan keagamaan yang dominan, termasuk karya Aristoteles, ditinjau kembali berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran Barat yang baru.
Dimulai pada abad ke-18, era Pencerahan menyaksikan lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan bersamaan dengan itu diadopsinya prinsip tersebut. nullius di verba – secara harafiah, “tidak mempercayai kata-kata siapa pun” – yang menjadi semboyannya Royal Society. Pendekatan sekuler juga semakin berkembang dalam memahami hakikat realitas dan, lebih jauh lagi, cara kita menjalani hidup.
Salah satu filsafat sekuler yang paling berpengaruh adalah eksistensialisme. Pada abad ke-20, Jean-Paul Sartre, tokoh kunci dalam eksistensialisme, menerima tantangan untuk memikirkan makna hidup tanpa menggunakan teologi. Sartre berargumentasi bahwa Aristoteles, dan mereka yang mengikuti jejak Aristoteles, mengalami semuanya secara back-to-front.
Eksistensialis melihat kita menjalani hidup dengan membuat pilihan yang tampaknya tak ada habisnya. Kita memilih apa yang kita kenakan, apa yang kita katakan, karier apa yang kita ikuti, apa yang kita yakini. Semua pilihan ini membentuk siapa kita. Sartre merangkum prinsip ini dalam rumusan “eksistensi mendahului esensi”.
Kaum eksistensialis mengajarkan kita bahwa kita sepenuhnya bebas menciptakan diri kita sendiri, dan karena itu sepenuhnya bertanggung jawab atas identitas yang kita pilih. “Efek pertama dari eksistensialisme,” tulis Sartre dalam esainya tahun 1946 Eksistensialisme adalah Humanisme, “adalah bahwa hal ini menempatkan setiap orang dalam kepemilikan dirinya sebagaimana adanya, dan menempatkan seluruh tanggung jawab atas keberadaannya berada di pundaknya sendiri.”
Pentingnya menjalani kehidupan yang autentik, kata para eksistensialis, adalah menyadari bahwa kita menginginkan kebebasan di atas segalanya. Mereka berpendapat bahwa kita tidak boleh menyangkal fakta bahwa kita pada dasarnya bebas. Namun mereka juga mengakui bahwa kita mempunyai begitu banyak pilihan mengenai apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan, sehingga hal ini merupakan sumber penderitaan. Penderitaan ini merupakan rasa tanggung jawab kita yang besar.
Kaum eksistensialis menyoroti sebuah fenomena penting: kita semua meyakinkan diri kita sendiri, pada titik tertentu dan sampai batas tertentu, bahwa kita “terikat oleh keadaan eksternal” untuk melepaskan diri dari penderitaan kebebasan kita yang tak terhindarkan. Percaya bahwa kita memiliki esensi yang telah ditentukan sebelumnya adalah salah satu keadaan eksternal tersebut.
Namun kaum eksistensialis memberikan serangkaian contoh lain yang mengungkap secara psikologis. Sartre bercerita tentang pengamatan seorang pelayan di sebuah kafe di Paris. Dia mengamati bahwa pelayan itu bergerak terlalu tepat, terlalu cepat, dan tampak terlalu bersemangat untuk mengesankan. Sartre percaya bahwa tindakan pelayan yang berlebihan adalah sebuah tindakan – bahwa pelayan tersebut menipu dirinya sendiri dengan menjadi seorang pelayan.
Dengan melakukan hal tersebut, kata Sartre, pelayan tersebut menyangkal dirinya yang sebenarnya. Dia malah memilih untuk mengambil identitas sesuatu selain makhluk yang bebas dan otonom. Tindakannya mengungkapkan bahwa ia menyangkal kebebasannya sendiri, dan pada akhirnya menyangkal kemanusiaannya sendiri. Sartre menyebut kondisi ini sebagai “itikad buruk”.
Kehidupan yang otentik
Bertentangan dengan konsepsi Aristoteles tentang eudaimonia, kaum eksistensialis menganggap bertindak secara otentik sebagai kebaikan tertinggi. Ini berarti tidak pernah bertindak sedemikian rupa sehingga menyangkal bahwa kita bebas. Saat kita menentukan pilihan, pilihan itu harus sepenuhnya menjadi milik kita. Kita tidak mempunyai esensi; kita hanyalah apa yang kita buat untuk diri kita sendiri.
Suatu hari, Sartre dikunjungi oleh seorang murid, yang meminta nasihatnya tentang apakah ia harus bergabung dengan pasukan Perancis dan membalas kematian saudaranya, atau tinggal di rumah dan memberikan dukungan penting bagi ibunya. Sartre yakin sejarah filsafat moral tidak akan membantu dalam situasi ini. “Kamu bebas, oleh karena itu pilihlah,” jawabnya kepada muridnya – “artinya, ciptakan”. Satu-satunya pilihan yang dapat diambil oleh sang murid adalah pilihan yang benar-benar merupakan pilihannya sendiri.
Kita semua mempunyai perasaan dan pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup kita, dan hal ini tidak semudah memihak pada penganut Aristoteles, eksistensialis, atau tradisi moral lainnya. Dalam esainya, Bahwa Mempelajari Filsafat berarti Belajar Mati (1580), Michel de Montaigne menemukan jalan tengah yang mungkin ideal. Ia mengusulkan “perencanaan kematian adalah perencanaan kebebasan” dan bahwa “dia yang belajar mati telah lupa bagaimana rasanya menjadi budak”.
Dengan gaya bercanda yang khas, Montaigne menyimpulkan: “Saya ingin kematian membawa saya menanam kubis, tetapi tanpa memikirkannya dengan cermat, dan apalagi kebun saya belum selesai.”
Mungkin Aristoteles dan kaum eksistensialis bisa sepakat bahwa hanya dengan memikirkan hal-hal ini – tujuan, kebebasan, keaslian, kematian – kita mengatasi keheningan karena tidak pernah memahami diri kita sendiri. Mempelajari filsafat, dalam pengertian ini, berarti mempelajari cara hidup.![]()
Tentang Penulis
Oscar Davis, Rekan Pribumi - Asisten Profesor dalam bidang Filsafat dan Sejarah, Universitas Bond
Artikel ini diterbitkan kembali dari Percakapan di bawah lisensi Creative Commons. Membaca Artikel asli.
buku_kesadaran