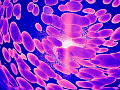Para deputi Sheriff yang mengenakan pakaian anti huru hara menyerang para demonstran di Los Angeles, California. Foto oleh David McNew / Getty Images
Kerusuhan dipicu oleh kematian George Floyd setelah dijepit ke tanah oleh lutut seorang perwira polisi Minneapolis telah meninggalkan bagian kota-kota AS yang tampak seperti zona pertempuran.
Malam demi malam, pengunjuk rasa yang marah telah turun ke jalan. Begitu juga dengan petugas polisi yang mengenakan perlengkapan kerusuhan penuh dan didukung oleh gudang senjata yang dapat dibanggakan oleh pasukan militer kecil mana pun: kendaraan lapis baja, pesawat kelas militer, peluru karet dan kayu, granat kejut, meriam suara dan tabung gas air mata.
Militerisasi departemen kepolisian telah menjadi fitur penegakan hukum domestik AS sejak serangan 9/11. Yang jelas dari putaran terakhir protes dan tanggapan, adalah bahwa meskipun ada upaya untuk mempromosikan de-eskalasi sebagai sebuah kebijakan, budaya polisi tampaknya terjebak dalam mentalitas "kita vs. mereka".
Menyiapkan musuh
Sebagai mantan perwira polisi 27 tahun dan a sarjana yang punya ditulis tentang pemolisian masyarakat yang terpinggirkan, Saya telah mengamati militerisasi polisi secara langsung, terutama pada saat konfrontasi.
Saya telah melihat, sepanjang dekade saya dalam penegakan hukum, Bahwa budaya polisi cenderung untuk mengistimewakan penggunaan taktik kekerasan dan kekuatan yang tidak bisa dinegosiasikan lebih dari kompromi, mediasi, dan resolusi konflik damai. Ini memperkuat penerimaan umum di antara petugas tentang penggunaan setiap dan semua cara kekuatan yang tersedia ketika dihadapkan dengan ancaman nyata atau yang dirasakan petugas.
Kami telah melihat permainan ini selama minggu pertama protes setelah kematian Floyd di kota-kota dari Seattle ke Flint ke Washington, DC
Polisi telah mengerahkan tanggapan militer terhadap apa yang mereka yakini secara akurat atau tidak akurat sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, properti pribadi, dan keselamatan mereka sendiri. Ini sebagian karena budaya kepolisian di mana para pemrotes sering dianggap sebagai "musuh." Memang mengajar polisi untuk berpikir seperti tentara dan belajar cara membunuh telah menjadi bagian dari latihan Program populer di kalangan beberapa petugas polisi.
Mempersenjatai
Militerisasi polisi, proses di mana lembaga penegak hukum telah meningkatkan gudang senjata dan peralatan mereka untuk ditempatkan dalam berbagai situasi, dimulai dengan sungguh-sungguh setelah serangan teroris pada 11 September 2001.
Pada tahun-tahun berikutnya, penegakan hukum domestik di Amerika Serikat memulai perubahan strategis ke arah taktik dan praktik yang menggunakan respons militer untuk kegiatan polisi rutin sekalipun.
Banyak dari ini dibantu oleh pemerintah federal, melalui Program 1033 Badan Logistik Pertahanan, yang memungkinkan transfer peralatan militer ke lembaga penegak hukum setempat, dan Program Hibah Keamanan Dalam Negeri, yang memberi dana kepolisian untuk membeli senjata dan kendaraan tingkat militer.
Kritik terhadap proses ini telah menyarankan bahwa pesan yang dikirim ke polisi melalui melengkapi mereka dengan peralatan militer adalah bahwa mereka sebenarnya berperang. Ini bagi saya menyiratkan bahwa perlu ada seorang musuh." Di kota-kota dan, semakin, pinggiran kota dan daerah pedesaan, musuh sering kali adalah "orang lain" yang dianggap cenderung kriminal.
Konsekuensi dari mentalitas polisi militer ini dapat mematikan, terutama bagi orang kulit hitam Amerika.
Sebuah studi dari kematian akibat keterlibatan polisi antara 2012 dan 2018 menemukan bahwa rata-rata, polisi membunuh 2.8 pria setiap hari di AS. Risiko kematian di tangan seorang perwira ditemukan antara 3.2 dan 3.5 kali lebih tinggi untuk pria kulit hitam dibandingkan dengan pria kulit putih.
Dan tampaknya ada korelasi antara militerisasi dan kekerasan polisi. SEBUAH 2017 studi menganalisis pengeluaran departemen kepolisian terhadap kematian yang melibatkan polisi. Meringkas mereka hasil di The Washington Post, penulis penelitian menulis: “Bahkan mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin dalam kekerasan polisi (seperti pendapatan rumah tangga, populasi keseluruhan dan kulit hitam, tingkat kejahatan-kejahatan dan penggunaan narkoba), lembaga penegak hukum yang lebih militeristik dikaitkan dengan lebih banyak warga sipil yang terbunuh. setiap tahun oleh polisi. Ketika sebuah county berubah dari tidak menerima peralatan militer hingga senilai $ 2,539,767 (angka terbesar yang masuk ke satu agensi dalam data kami), lebih dari dua kali lebih banyak warga sipil kemungkinan meninggal di county itu pada tahun berikutnya. "
Dan bukan hanya individu yang menderita. Ilmuwan perilaku Denisa Herd telah mempelajari efek komunitas dari kekerasan polisi. Menulis di Boston University Law Review awal tahun ini, dia menyimpulkan bahwa "pertemuan kekerasan dengan polisi menghasilkan efek riak yang kuat dari berkurangnya kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang hanya tinggal di daerah di mana tetangga mereka terbunuh, terluka, atau mengalami trauma psikologis."
Trauma dari video George Floyd dalam kesulitan yang jelas sementara seorang petugas berseragam berlutut di lehernya terbukti dalam reaksi yang diprovokasi.
Kebutuhan untuk mengatasi eskalasi konfrontasi polisi - baik selama protes dan dalam pertemuan individu - adalah fokus dari dorongan besar terakhir untuk reformasi polisi, setelah pembunuhan seorang pria kulit hitam yang tidak bersenjata di Ferguson, Missouri, pada tahun 2014. Seperti halnya kasus ini George Floyd, itu mengarah ke adegan-adegan kekerasan di mana para demonstran menghadapi para perwira militer.
Hanya beberapa bulan setelah kerusuhan Ferguson, Presiden Obama mengaturnya Gugus Tugas pada Pemolisian Abad 21. Ini merekomendasikan implementasi pelatihan dan kebijakan yang “menekankan pada eskalasi.” Ia juga meminta polisi untuk menggunakan taktik selama protes "yang dirancang untuk meminimalkan penampilan operasi militer dan menghindari penggunaan taktik dan peralatan provokatif yang merusak kepercayaan sipil."
Dengan bukti beberapa hari terakhir, sejumlah departemen kepolisian gagal mengindahkan pesan tersebut.
Tentang Penulis
Tom Nolan, Associate Professor Sosiologi, Universitas Emmanuel
Artikel ini diterbitkan kembali dari Percakapan di bawah lisensi Creative Commons. Membaca Artikel asli.


 Para deputi Sheriff yang mengenakan pakaian anti huru hara menyerang para demonstran di Los Angeles, California.
Para deputi Sheriff yang mengenakan pakaian anti huru hara menyerang para demonstran di Los Angeles, California.